Pendahuluan
Proses perwahyuan al-Qur`an sudah selesai sejak berabad-abad silam. Beriringan dengan berhentinya proses perwahyuan, al-Qur`an hanya teks “mati” sehingga tidak bisa berkembang lagi guna merespons perkembangan kehidupan manusia sebagaimana terjadi pada saat proses perwahyuan. Di sisi lain, perkembangan kehidupan manusia semakin berkembang, bahkan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pada saat proses perwahyuan. Tidak heran bila ada jargon terkenal yang mendeskripsikan fakta itu, yaitu al-nusūs mutanāhiyah wa al-waqā`i’ ghayr mutanāhiyah.
Sejatinya jargon tersebut bukan hanya merujuk pada al-Qur`an an sich, tetapi juga pada hadis. Hanya saja mayoritas umat Islam terlajur menganggap al-Qur`an sebagai sumber teks Islam paling utama. Oleh sebab itu, meski ayat-ayat al-Qur`an mustahil bertambah, tetapi penafsiran-penafsiran terhadapnya tetap berlangsung hingga saat ini dan perlu dikaji ulang serta dikembangkan agar fungsinya sebagai problem solver perkembangan kehidupan manusia tetap berjalan sebagaimana pada berlaku saat proses perwahyuan.
Sejak awal Islam hingga sekarang penafsiran beraneka ragam sesuai dengan kapasitas intelektual dan kecenderungan sang penafsir. Keanekaragaman penafsiran tidak hanya membuktikan fleksibelitas dan elastisitas kandungan al-Qur`an terhadap perkembangan kehidupan manusia, tetapi juga membuktikan adanya legitimasi keabsahan untuk menafsirkan al-Qur`an sesuai dengan keinginan masing-masing. Meskipun statemen ini kontras dengan keyakinan mayoritas kalangan Sunni, tetapi statemen tersebut justeru sesuai dengan fakta di lapangan.
Salah satu dari aneka ragam penafsiran itu adalah penafsiran kontekstual. Penasiran ini semakin hari semakin sering didiskusikan. Ia merupakan sebuah usaha untuk tidak mengkultuskan karya-karya penafsiran yang telah ada. Sebab dengan adanya penafsiran ini, karya-karya penafsiran yang telah ada sebelumnya hanya sebagai referensi yang bila kandungannya masih sesuai dengan tuntutan zaman, maka akan diambil dan dikembangkan, tetapi bila tidak, maka karya-karya itu hanya seperti tumpukan bundelan kertas yang hanya bisa menghiasi koleksi perpustakaan sebagai kekayaan khazanah keilmuan Islam. Continue reading ‘Tafsir Kontekstual’
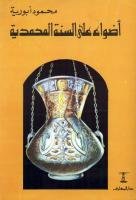
 Pada pemilu pertama tahun 1955, dengan meraup 20, 29 % suara, Masyumi menjadi partai Islam terkuat melebihi perolehan suara partai-partai Islam lainnya seperti
Pada pemilu pertama tahun 1955, dengan meraup 20, 29 % suara, Masyumi menjadi partai Islam terkuat melebihi perolehan suara partai-partai Islam lainnya seperti
Recent Comments